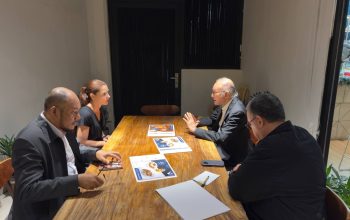Wali Nanggroe, Bencana, dan Ujian Moral Negara
KoranAceh.Net | Editorial – Pernyataan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, agar seluruh bantuan bencana dapat masuk ke Aceh tanpa hambatan, bukan sekadar seruan kemanusiaan. Ia adalah peringatan politik—dan sekaligus ujian moral bagi Jakarta: apakah negara ini benar-benar belajar dari sejarah Aceh, atau kembali mengulang pola lama, memusatkan kontrol sambil mengabaikan penderitaan di daerah.
Ketika Wali Nanggroe menyebut bencana ekologis sebagai “tsunami kedua”, ia sedang menunjuk langsung pada akar masalah yang selama ini disangkal: kerusakan hutan, ekspansi industri ekstraktif, dan tata kelola lingkungan yang tunduk pada kepentingan modal. Tsunami pertama adalah takdir alam. Tsunami kedua adalah hasil kebijakan.
Jakarta Melunak, Tapi Belum Tentu Mendengar
Melunaknya sikap Jakarta terhadap masuknya bantuan internasional non-pemerintah patut dicatat. Namun pertanyaan mendasarnya bukan apakah bantuan boleh masuk, melainkan mengapa sebelumnya harus ditahan.
Refleks negara yang mencurigai solidaritas internasional—bahkan saat rakyatnya sendiri terendam banjir dan longsor—adalah cermin lama dari sentralisme kuasa yang alergi terhadap kontrol moral dari luar. Dalam konteks ini, perubahan sikap Jakarta lebih tepat dibaca sebagai koreksi taktis, bukan perubahan paradigma.
Jakarta tidak secara terbuka mengakui tekanan. Tapi negara juga tahu: mengabaikan Wali Nanggroe secara terang-terangan berarti menginjak simbol perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki. Maka yang terjadi adalah kompromi setengah jalan—izin dibuka, tetapi tetap dengan pagar birokrasi dan kontrol pusat.
Wali Nanggroe: Wibawa yang Tidak Bisa Diperintah, Tapi Tak Bisa Diabaikan
Secara hukum, Wali Nanggroe memang tidak memegang kekuasaan eksekutif. Namun dalam politik Aceh, ia adalah otoritas moral tertinggi. Ia berdiri di atas garis partai, melampaui siklus pemilu, dan berbicara atas nama sejarah, trauma, dan masa depan Aceh.
Justru karena tidak punya instrumen koersif, wibawanya bekerja melalui tekanan etis. Ketika Wali Nanggroe berkata, “Saya tidak akan tinggal diam”, itu bukan ancaman kekuasaan—itu peringatan legitimasi. Negara boleh mengabaikan pejabat, tetapi mengabaikan simbol berarti menggerus kepercayaan.
Ekologi: Medan Pertarungan Baru Aceh–Jakarta
Yang paling mengganggu bagi Jakarta bukan soal bantuan, melainkan agenda ekologis yang dibawa Wali Nanggroe. Seruannya agar hutan tidak ditebang dan sawit dibatasi adalah tantangan langsung terhadap model pembangunan nasional yang ekstraktif.
Selama ini, Aceh sering diposisikan sebagai objek: objek dana otsus, objek investasi, objek stabilitas. Dengan menjadikan hutan, DAS, dan satwa liar sebagai isu utama, Wali Nanggroe memindahkan pertarungan ke medan yang tidak bisa dibungkam dengan jargon kedaulatan. Ini adalah isu lintas generasi, lintas batas, dan lintas rezim.
Ketika ia mengatakan “Aceh bisa maju tanpa menghancurkan hutannya”, itu bukan slogan hijau. Itu kritik ideologis terhadap pembangunan yang mengorbankan alam dan manusia demi pertumbuhan semu.
Negara Diuji: Belajar atau Mengulang?
Aceh tidak sedang meminta belas kasihan. Aceh sedang menuntut koherensi negara: Jika negara bicara soal ketangguhan bencana, maka lindungi hutan. Jika negara bicara soal pemulihan, maka buka ruang solidaritas. Jika negara bicara soal perdamaian, maka hormati simbol-simbolnya.
Mengabaikan peringatan Wali Nanggroe berarti memilih jalan pendek kekuasaan, bukan jalan panjang keadilan ekologis. Dan sejarah Aceh menunjukkan: setiap kali pusat memilih jalan pendek, biayanya selalu dibayar mahal—oleh rakyat, oleh alam, dan oleh legitimasi negara itu sendiri.
Penutup: Ini Bukan Tentang Aceh Saja
Yang dipertaruhkan bukan hanya Aceh. Yang diuji adalah kemampuan Indonesia menjadi negara yang mendengar, bukan sekadar memerintah.
Jika Jakarta gagal membaca pesan ini, maka “tsunami kedua” yang diperingatkan Wali Nanggroe bukan hanya akan datang kembali ke Aceh—tetapi akan menjadi metafora kegagalan nasional dalam mengelola alam dan keadilan. Dan saat itu tiba, negara tak bisa lagi berkata: tidak tahu. []